
Pendahuluan
Dalam setiap agama mempunyai peraturan dan ketentuan. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw juga mempunyai aturan dan ketetapan. Dalam Islam sendiri dikenal istilah syariat yang berarati aturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam.
Allah Swt menurunkan syariat kepada hamba-hambanya tidak lain sebagai rahmat yang diberikan secara merata, tanpa terkecuali. Setiap hamba-Nya baik itu kaya, miskin, orang terpandang, atau orang bawahan semuanya diberi kerahmatan berupa syariat yang sama. Kehidupan manusia, khususnya umat Islam diatur dan dibungkus dalam syariat yang diturunkan Allah dan diajarkan Nabi Muhammad Saw, baik berupa perintah, larangan, anjuran dan sebagainya.
Ketetapan atau beban yang telah diberikan ke hamba-hamba-Nya, terkadang manusia sendiri dalam menjalankan hukum-hukum itu tergantung kemampuan, kondisi dan tingkatannya. Adakalanya dilakukan orang yang berada dalam kondisi normal, ada kalanya dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi tidak normal atau diluar kemampuan untuk menjalankan hukum-hukum yang ditetapkan. Maka dari itu, Allah memberikan rukhshah (Keringanan hukum) bagi hamba-Nya pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menjalankan syariat secara normal.
Pengertian Mahkum Fih, Rukshah dan Azimah
Mahkum Fiih adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari’.[1] Dalam hukum syari, ada beberapa kriteria hukum, di antaranya wajib, sunah (nadb), haram (tahrim), makruh (karahah), dan Kebolehan (Ibahah). Semua hukum syariat wajib berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dari segi tuntutan, atau perintah memilih (takhyir), atau ketetapan (al-wadh’u). Kebanyakan ulama tidak berselisih pendapat bahwa hakikat hukum syariat merupakan khihtab Allah yang berisi amal perbuatan mukalaf yang berisi tuntunan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani’ bagi sesuatu.
Azimah adalah hukum-hukum umum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sejak semula, yang tidak dikhususkan oleh kondisi dan oleh mukallaf. Rukhsah terambil dari bahasa Arab yang berarti meringankan dan memudahkan.[2] Secara Istilah rukhshah adalah hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan.[3] Rukshah digunakan sebagai pembebasan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan hukum yang bersifat umum (azimah) dalam keada-an dlarurah, baik dalam mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.[4]
Di antara rukhsah itu adakalanya yang membolehkan larangan ketika adanya dlarurat atau kebutuhan. Contohnya, orang yang ditimpa kelaparan dan kehausan yang sudah tidak dapat ditahan dan itu terjadi ditengah hutan atau tidak ada apapun kecuali bangkai, babi, dan sebagainya yang dilarang oleh syara’ maka, memakan yang dilarang syariat tidak berdosa dan diperbolehkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه (Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melaumpaui batas, maka tidak ada dosa baginya).
Dalam Qawaidul Fiqhiyah juga dijelaskan الضرورات تبيح المحظورات yang berarti dlarurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Di antara hukum rukshah yang lain yaitu, kebolehan atas orang-orang mukallaf meninggalkan kewajiban ketika ada udzur, yang mengakibatkan kesulitan amat sangat untuk menunaikannya. Ada juga membenarkan sebagaian akad yang bersifat pengecualian, tidak terpenuhinya syarat-syarat umum tentang jadi dan syahnya akad, tetapi berlaku bagi hubungan manusia dan menjadi sebagaian dari kebutuhann manusia, seperti akad salam.
Syarat Sahnya Tuntutan dengan Perbutan
Permasalahan syahnya tuntutan dengan perbuatan, di dalam hukum syariat diisyaratkan dengan tiga syarat :[5]
Pertama, perbuatan benar-benar diketahui oleh mukallaf, baik dari segi hukum syara, dari segi tata cara mengerjakan, dan sebagainya supaya mukallaf dapat mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan. Atas dasar tersebut, maka nash-nash dalam Al-Qur’an yang penjelasanya masih global tidak sah menuntut mukallaf kecuali setelah ada penjelasan dari Rasulullah Saw. Contohnya, firman Allah اقيموا الصلاة “Dirikanlah sholat” ayat tersebut masih sangat global untuk memerintah orang muslim sholat. Al-Qur’an belum menjelaskan rukun-rukun shalat, syarat-syaratnya, dan cara menunaikannya. Dengan adanya penjelasan dari Nabi Muhammad Saw, صلوا كما رأيتمني اصلي “Sholatlah kamu sebagai mana kamu melihatku sholat”, maka tuntutan bagi mukallaf syah dengan perbuatan yang dilakukan mukallaf, yaitu sholat.
Sholat hanya selah satu cntoh saja, selain sholat ada haji, zakat, puasa, dan sebagainya kebanyakan dalam Al-Qur’an masih global penjelasannya, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw, yang dapat kita temukan dalam sunah-sunahnya. Tidak sah menggunakan tuntutan dengan nash atau dalil yang global tanpa melihat penjelasan-penjelasan untuk mengerjakan tuntutan tersebut, utamanya penjelasan dari Nabi Muhammad Saw. Allah Swt telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad Saw untuk menjelaskan kepada umat manusia segala apa yang Allah firmankan dan turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam Surah an-Nahl ayat 44 Allah berfirman,
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
“Dan kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
Rasulullah Saw telah menjelaskan keglobalan nash di dalam nash di dalam Al-Qur’an dengan sunahnya yang bersifat ucapan dan perbuatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwasanya tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan.[6]
Kedua, diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang punya kekuasaan menuntut, atau dari orang-orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf. Dengan pengetahuan orang-orang yang berkuasa menuntut menjadi, sebab bahwa permulaan pembahasan mengenai setiap dalil syara merupakan kehujahan yang dapat dipakai oleh orang-orang mukalaf. Artinya bahwa hukum-hukum yang menunjukkan makna hukum merupakan sebab dalam hal undang-undang buatan itu diberi mahkota dengan sutera yang murni, yang menunjukan bahwa Hakim itu mengeluarkan undang-undang atas dasar keputusan majelis kabinet dan dengan persetujuan parlemen. Hal tersebut bertujuan supaya orang-orang mukallaf mengetahui bahwa undang-undang itu keluar dari orang yangb mempunyai kekuasaan membuat hukum atau dari orang yang wajib diikuti tuntutannya, sehingga meraka akan berupaya melaksanakannya.
Atas dasar pembuatan undang-undang yang bersifat ketetapan (wadh’i), maka manusia dianggap mengetahui undang-undang lantaran pemudahan tentang kemungkinan mengetahuinya. Tidak ada anggapan bahwa masing-masing orang mukallaf itu mempunyai pengetahuan terhadap undang-undang dalam bentuk perbuatan atau bukan. Setiap hukum syara bagi mukallaf memungkinkan mengetahui dalilnya, dan mengetahui bahwa dalilnya itu adalah hujah syar’iyah atas mukallaf untuk mengikuti hukum yang di-istimdadkan (dibentangkan satu diambil) dari padanya, baik pengetahuan itu diambil sendiri atau lantaran bertanya kepada cendekiawan mengenai hal tersebut.
Ketiga, perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin bisa dilakukan atau ada kemampuan mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dari syarat tersebut bercabanglah dua hal, yaitu :
Tidak sah membebani hal yang mustahil, baik mustahil itu datang dari dirinya, atau karena sesuatu yang lain. Mustahil yang datang dari dirinya, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditemukan wujudnya oleh akal, seperti mengumpulkan dua hal yang berlawanan. Contohnya, mewajibkan suatu perbuatan dan mengharamkan dalam satu waktu.
Mustahil karena sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang dapat ditemukan wujudnya oleh akal, tetapi tidak berlaku rumus alam dan kebiasaan yang berlaku bagi wujudnya. Seperti, terbangnya manusia tanpa alat penerbangan atau adanya tanaman tanpa biji. Sesuatu yang tidak dapat ditemukan wujudnya mukallaf tidak tidak akan mampu melakukannya. Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan dan kesanggupannya.
Menurut syara tidak sah membebani mukallaf supaya selain dia mengerjakan perbuatan atau mencegahnya. Maksudnya melakukan atau meningglkan oleh selain dia itu berarti bukan hal yang mungkin atau dikuasai oleh dirinya. Misalnya, seseorang tidak dituntut supaya bapaknya mengeluarkan zakat untuk dirinya dan saudaranya melakukan shalat untuk dirinya. Segala sesuatu yang mukallaf dituntut dengan itu, yang berupa kekhususan bagi lainnya merupakan nasihat, perintah kebaikan dan larangan melakukan sesuatu yang mungkar. Hal tersebut termasuk perbuatan yang dikuasai atau dapat dilaksanakan sendiri oleh mukallaf.
Menurut syara tidak sah membebani mukiallaf dengan hal-hal yang bersifat watak kemausiaan yang merupakan sebab-sebab sifat kenalurian manusia. Mukallaf tidak lagi mumpunyai jalan untuk mengusahakannya, seperti terbekas ketika luka, merak ktika malu, benci, duka, suka, dan takut ketika ada sesbab-sebabnya. Ada tidaknya semua itu tunduk kepada undang-undang alam, bukan tunduk pada kehendak mukallaf dan usahanya. Semua itu keluar daripada kemampuannya, dan bukan hal yang mungkin bisa dilakukan olehnya.
Apabila di sebagian nash terdapat beberapa sesuatu yang mengandung beban suatu perkara di luar kemampuan manusia, maka hal tersebut bukan menurut lahirnya. Contohnya, penggalan sabda Rasulullah Saw لاتغضب “jangan marah”, secara lahiriyahnya beban tersebut bersifat naluri, bukan bersifat usaha, yaitu mehan marah ketika ada faktor-faktor yang mendorong untuk marah, tetapi mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan amarah dari pergolakan jiwa dan manifestasi keinginan untuk membalas. Jadi yang dimaksud di sini yaitu tahanlah ketika dirimu marah, dan jagalah dirimu dari pengaruh yang jelek.
Pendapat Ulama tentang Hukum Menggunakan Rukshah
Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan rukhsah itu tergantung pada bentuk uzur boleh jadi wajib, sunnat dan hak.[7] Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158: “Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya, mengerjakan antara keduanya (mengerjakan sa’i). Maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”.
Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa rukshah itu wajib. Ketika kita dalam kondisi tertentu dan kondisi tersebut mendapatkan rukhsah, maka wajib dilakukan. Ada juga ruksah yang berarti sunah, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 203 : “Dan berdzikirlah kepada Allah dan pada hari yang ditentukan jumlahnya (hari tasyriq) . Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan Barangsiapa yang ingin mengakhirkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya. (yakni) bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya”. Ulama Hadis juga menjelaskan ان لله یود ان یؤتي رخصھ كما یحب ان یؤتي عزائمه “Sesungguhnya Allah sangat ingin memberikan rukhsahnya sebagaimana juga memberikan azimahnya”.[8]
Pernyataan di atas dapat memberikan dua pemahaman. Pertama, menggunakan rukhsah dapat menghapus dosa dan menghilangkan kepicikan. Kedua, mengumpul antara rukhsah tidak menguatkan wajib atau sunat kepada azimah (yang terpokok), bukan rukhsah secara dhahirnya. Demikian keterpaksaan pada hukum yang tidak halal, sebagaimana yang ditetapkan untuk memelihara jiwa maka keringanan baginya memakan bangkai, mengurangi kesulitan, jika cemas adanya urusan menghidupkan jiwa atau dirinya.
Menurut ulama Hanafiah rukhsah dibagi menjadi dua bagian, yaitu rukhsah tarfih (keringanan yang enak) dan rukshah isqath (keringanan yang menggugurkan).[9] Rukhsah tarfih adalah keringanan atau rukhsah yang masih mendapat ketetapan hukum azimah dan masih berlakunyan dalil hukum asli, tetapi diperbolehkan meninggalkan, sebagai keringanan dan menyenangkan mukallaf. Contohnya, orang yang dipaksa mengucapkan kata yang kafir, dipaksa merusak harta orang lain, dan berbuka di siang hari pada bulan Ramadhan.
Bagian kedua yaitu rukshah isqat memiliki pengertian rukshah yang mengakibatkan tidak berlakunya lagi hukum azimah. Keadaan yang menuntut keringanan menggugurkan hukum azimah, sehingga hukum yang dipakai murni hukum rukshah. Contohnya, memakan bangkai dan meminum khamr ketika dalam keadaan terpaksa atau lapar dan haus yang tidak bisa ditahan, sedangkan dalam kondisi tersebut tidak ada makanan dan minuma lain atau biaya untuk membeli makanan dan minuman halal. Contoh lain adalah meng-qashar dan jama’ shalat dalam perjalanan, hukum yang dipakai bukan hukum sholat seperti biasanya, tetapi hukum sholat dengan cara qashar atau jama’.
Menurut pendapat al-Syathibi bahwa hukum rukhsah adalah boleh atau hak secara mutlak.[10] Ada tiga alasan dalam hal tersebut. Pertama, disamakan dengan dalil-dalil yang mengurangi kepicikan dan dosa-dosa selain yang dikehendaki urusan secara keseluruhan dengan mengutamakan keringanan.[11] Kedua, rukhsah itu asalnya hanya keringanan atau mengangkat kesulitan sehingga mukallaf mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum ‘azimah atau mengambil rukhsah, dengan dasar kebolehan meng-qashar sholat, dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 101, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Alasan ketiga yaitu, kalau menggunakan rukhsah itu diperintahkan baik dalam bentuk wajib atau sunnat, maka hukumnya akan berubah menjadi azimah, tidak lagi rukhsah, karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilhan lain. Maksudnya hukum yang dipakai tetap hukum rukshah, karena wajib atau sunnah menggunakan hukum rukshah, maka hukum itu menjadi azimah dalam segi nama hukumnya, pelaksanaannya tetap menggunakan hukum rukshah dari hukum azimah yang asal.
Rukhsah menurut Abu Ishak Al Syatiby dalam Al-Muwafuqat dalam menggunakannya sesuai tingkat masyaqqah atau kesukaran melakukan hukum azimah, yaitu, dalam menghadapi kesukaran itu seorang mukallaf tidak mungkin melakukan kesabaran dalam menghadapinya. Umpamanya melakukan puasa karena khawatir mencelakakan dirinya atau orang makan daging babi karena terpaksa dan tidak menemukan makanan halal yang lain.
Dalam menghadapi kesukaran itu mukallaf dapat berlaku sabar karena secara langsung tidak akan membahayakan diri pelakunya, rukhsah dalam bentuk. Ini kembali kepada hak hamba untuk memperoleh kemudahan dari Allah dan kasih sayangnya.[12]
Pengaruh tuntutan mahkum fih dengan adanya rukshah
Semua perbuatan mukallaf harus berdasar pada hukum yang telah disyariatkan. Mukallaf memiliki beban yang dituntut kepadanya oleh syariat, baik itu perintah, perintah memilih, atau larangan. Tuntutan yang diberikan kepada mukallaf semua sudah tertulis dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah, maka mukallaf wajib untuk mengikuti dan merealisasikan beban atas tuntutannya sesuai Al-Qur’an maupun as-Sunnah.
Beban dan tuntutan yang diberikan kepada mukallaf tidak semua bisa dilaksanakannya, ketika dalam kondisi tertentu. terkadang mukallaf mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan beban dan tuntutannya. Syariat yang hakikatnya untuk kemaslahatan umat, baik dalam mengambil kemnfaatan dan menjunjung tinggi fitrah manusia dengan memelihara dan memperhatikan manusia dalam kondisi biasa atau diluar kemampuan untuk melaksanakan tuntutan dan beban yang diperolehnya.
Adanya konsep rukshah dan azimah dalam hukum syari’at membuat mukaallaf tidak akan merasa kesusahan untuk menjalankan tutntutan atau bebannya, baik dalam kondisi biasa memungkinkan dapat menjalankan tuntutan dan bebannya secara sempurna, atau dalam kondisi yang tidak menentukan untuk melakukannya secara sempurna, bahkan sama sekali.
Rukhsah sebagai keringanan dan pengaruh terhadap mahkum fih yang diberikan oleh Allah sebagai pembuat hukum kepada orang-orang mukallaf dalam suatu keadaan tertentu yang berlaku terhadap orang mukallaf, maka rukhsah dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, dari segi bentuk asalnya yaitu, menjadikan keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang harus ditinggalkan, dalam bentuk asal ini perbuatan terlarang dan haram hukumnya (azimah), oleh karena kondisi darurat dan hajat, maka perbuatan terlarang itu menjadi boleh hukumnya. Kedua, rukhsah untuk meninggalkan perbuatan yang menurut hukum azimahnya adalah wajib atau Sunat yang menurut asalnya dalam keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya dan akan membahayakan terhadap dirinya, dibolehkan meninggalkannya. Ketiga, Rukhsah dalam meninggalkan hukum-hukum yang berlaku terhadap umat sebelum Islam yang dinilai terlaluberat untuk dilakukan umat Muhammad SAW, seperti membayar zakat ¼ dari harta, bunuh diri sebagai cara tobat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara membersihkannya, dan keharusan sembahyang di masjid yang berlaku bagi syariat Nabi Musa As. Keempat, rukhsah dalam bentuk melegalisasikan beberapa bentuk akad yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti jual beli salam, dalam hal muamalah.
Rukhsah ditinjau dari bentuk keringanan yang diberikan ada tujuh bentuk. Pertama, keringanan dalam bentuk menggugurkan kewajiban seperti bolehnya meninggalkan shalat Jum’at Haji, Umrah, Haji dan Jihad dalam keadaan uzur. Kedua, keringanan dalam mengurangi kewajiban umpama menqasar salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang dalam perjalanan. Ketiga, keringanan dalam mengganti kewajiban seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamun karena tidak ada air ,dan seterusnya. Keempat, keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban, seperti pelaksanaan shalat zhuhur dalam waktu ashar pada jama’ takhir karena dalam perjalanan. Kelima, keringanan dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban, seperti membayar zakat fitrah semenjak awal bulan Ramadhan, mengerjakan shalat ashar pada waktu dhuhur kalau jama’ taqdim di perjalanan. Keenam, keringanan dalam bentuk mengubah kewajiban seperti cara-cara pelaksanaan shalat dalam perang yang berubah dari bentuk biasanya yang disebut shaf khauf. Ketujuh, keringanan dalam bentuk membolehkan mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena uzur sebagaiman tersebut di atas.[13]
Dengan dasar adanya rukhsah, maka dapat dilihat asas penerapan syariat yang disepakati ulama ushul yakni syariat tidak memberatkan dan tidak mempersempit, tidak memperbanyak tuntutan, dan dilaksanakan secara bertahap.عدم الحرج yaitu, meniadakan kesempitan dan kesukaran, maka dalam hal ini tuntutan dan syariat dilaksanakan secara bertahap dibolehkan hal yang haram disebabkan karena darurat. Misalnya, memakan daging babi apabila dalam keadaan darurat memakannya karena dia dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali babi itu saja. Andai kata ia tidak memakannya dia akan meninggal. Maka berlakulah rukhsah baginya.
يرفع تكالف yaitu, menghilangkan beban yang berat berlaku pada syariat terdahulu. Misalnya mencuci pakaian yang kena najis dengan air suci, sebagai rukhsah terhadap tata cara mensucikan pakaian yang kena najis menurut syariat sebelum Islam, yaitu memotong pakaian yang kena najis itu lalu bertaubat sebagai rukhsah terhadap tata cara menyatukan penyesalan dari suatu perbuatan maksiat dengan bunuh diri, sebagaimana dilakukan oleh umat terdahulu.
Asas Tadarruj (bertahap) Ayat Al-Quran sendiri turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segeap surah, ayatayatnya selama ± 22 tahun, salah satu hikmahnya untuk mempermantap bacaan dan mempermudah hafalan Rasulullah Saw serta sahabat-sahabatnya, dengan maksud agar kandungannya mudah, dihayati dan diamalkan secara bertahap sampai pada puncak kesempurnaan.[14] Rukshah juga berperan bagi mukallaf dalam keadaan darurat (dlarurah) diper-bolehkan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Sesuai yang sudah dijelaskan di atas dalam kaidah fikih الضرورات تبيح المح “Dlarurah-dlarurah itu membolehkan segala yang dilarang”. Zhahiriyah, Abu Yusuf, Abu Ishak al-Syayrazi dari golongan Syafiiyyah dan satu pendapat dari golongan Hanabilah, dan satu riwayat dari AbuYusuf, mengatakan bahwa diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan terpaksa atau bagi orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang haram, seperti me-makan bangkai, darah, daging babi, memi-num khamar atau mengambil harta orang lain, maka orang tersebut tidak berdosa.[15]
Untuk batasan dlarurah sendiri beberapa ulama memberikan penjelasan. menurut Mu-hammad Abu Zahrah kekhawatiran terhadap kehidupan bila tidak melakukan hal yang dilarang atau khawatir hilangnya harta.[16] Al-Zarkasyi mendefinisikan bahwa dlarurah adalah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang maka ia akan binasa, atau mendekati binasa. Ulama Syafiiyyah mendefinisikan dlarurah adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit, atau terpi-sahnya dengan rombongan perjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengedarai kendaraan jika ia tidak ma-kan, dan ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan yang ada hanya makanan yang haram, maka ketika itu ia wajib memakan makan yang haram tersebut.[17]
Dari penguraian bahasan diatas dapat dipahami bahwa rukhsah dan azimah adalah dua hal yang saling berkaitan namun untuk merealisir tujuan hukum tetap mengutamakan kemaslahatan manusia baik dari kebutuhan daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Dimana melalui rukhsah itu mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum atau pembebanan hukum sesuai yang disanggupi baik bersifat ibadah maupun muamalah.
Kesimpulan
Semua mukallaf mempunyai beban dan tuntutan yang harus dilakukan, perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutanya harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat, karena akan mempengaruhi sah tidaknya perbuatan yang dilakukan. Tuntutan bagi mukallaf kadang sulit untuk dilakukan secara sempurna bahkan sama sekali tidak bisa melakukannya dalam kondisi tertentu. Adanya konsep rukshah dan azimah dalam syariat membuat mukallaf tidak kebingungan saat kondisi tertentu, baik karena dlarurat, ada hajat tertentu dan sebagainya.
Dalam keadaan biasa dan tidak ada hal yang mencegah mukallaf untuk melaksanakan tuntutannya, maka hukum azimah yang berlaku baginya. Ketika mukallaf dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan tuntutannya baik sama sekali atau hanya kurang sempurna, maka hukum rukshah yang berlaku bagi dirinya. Allah begitu sayang terhadap hambanya, Dia menetapkan syariatb yang harus ditaati seluruhnya tetap ada dalam syariat tersebut memperhatikan kemaslahatan hukum bagi hamba-Nya.
Daftar Pustaka
Abu Zahrah, Muhammad. Ushûl Fiqh (Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabi).
al-Ma’luf, Abu Luwis. 1997. al-Mumjid fi al-luglat wa al-a’lum, (Bairut Libanon, Thab’at Jadidah Munaggahat)
al-Zuhayli, Wahbah. (al-Dlarûrah al-Syar‘iyyah).
Bieh, Al-Khudari. 1982. Ushul Fikih Alih Bahasa Said Al-Syekh Muhammad Hamid. (Pekalongan: Raja Murak).
Departemen Agama Republik Indonesia.1992/1993. Al-Quran dan Terjemahnya, Ensiklopedia Islam, jilid III.(Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam Proyeek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama IAIN).
Khalaf, Abdul Wahab. 1994. Kaidah-Kaidah Hukum Islam.(Jakarta: PT Raja Garfindo Persada).
Musyarifah, Athiyah. 1996. Al Qadaufi Al Islam. (Syarikat Al Syarq Al Ausat).
Qudamah, Ibn.1969 .al-Mughni (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah).
Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fikih, Ed.I, Jld.I. (Jakarta: Kencana).
Zulbaidah. 2015. Relevansi Dlarurah Dengan Rukhshah Dalam Penetapan Hukum.Syara ‘Asy-Syari‘Ah Vol. 17.
[1] Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada), h. 201.
[2] Abu Luwis al-Ma’luf, al-Mumjid fi al-luglat wa al-a’lum, (Cet.XXVI, Bairut Libanon, Thab’at Jadidah Munaggahat, 1997), h. 254.
[3] Ibid, Abdul Wahab Khalaf, h. 189.
[4] Zulbaidah, Relevansi Dlarûrah Dengan Rukhshah Dalam Penetapan Hukum, Syara‘Asy-Syari‘Ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, h. 174.
[5] Ibid, Abdul Wahab Khalaf, h. 203
[6] Ibid, Abdul Wahab Khalaf, h. 204.
[7] Al-Khudari Bieh, Ushul Fikih, Alih Bahasa Said Al-Syekh Muhammad Hamid, (Pekalongan: Raja Murak, 1982), h. 78.
[8] Ibid, h. 77-78
[9] Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, h. 192
[10] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Ensiklopedia Islam, jilid III, (Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam Proyeek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama IAIN), 1992/1993, h. 49.
[11] Ibid, h. 42
[12] Al-Khudari Bieh, Ushul Fikih, Alih Bahasa Said Al-Syekh Muhammad Hamid, (Pekalongan: Raja Murak, 1982), h. 87.
[13] Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, Ed.I, Jld.I, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 356.
[14] Athiyah Musyarifah,Al Qadaufi Al Islam,(Syarikat Al Syarq Al Ausat, 1996), h. 66.
[15] Wahbah al-Zuhayli, al-Dlarurah al-Syar‘iyyah. h. 289.
[16] Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Fiqh (Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabi.), h. 45.
[17] Ibn Qudamah, al-Mughni (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah. 1969), h. 306.
(Agoy)






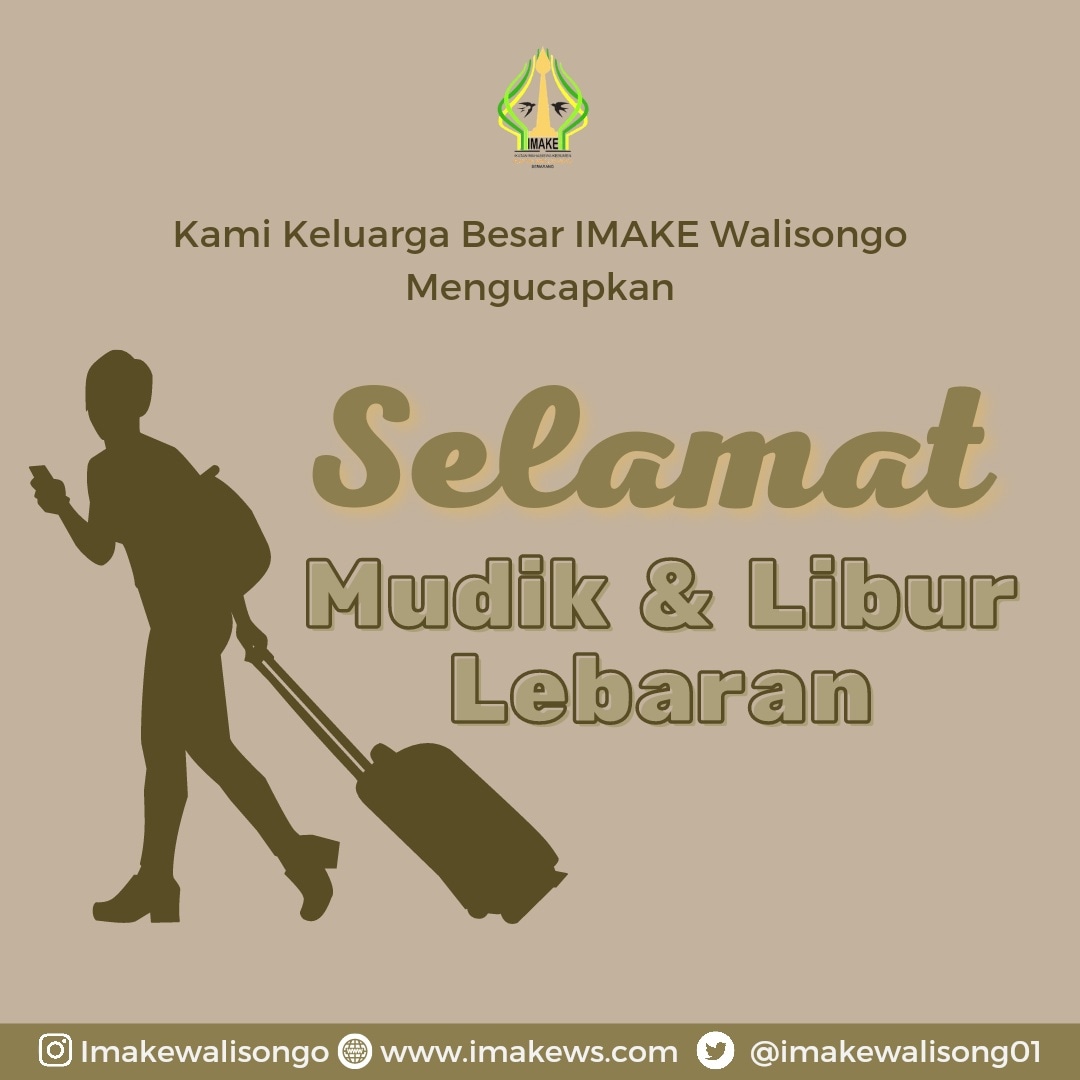







COMMENTS